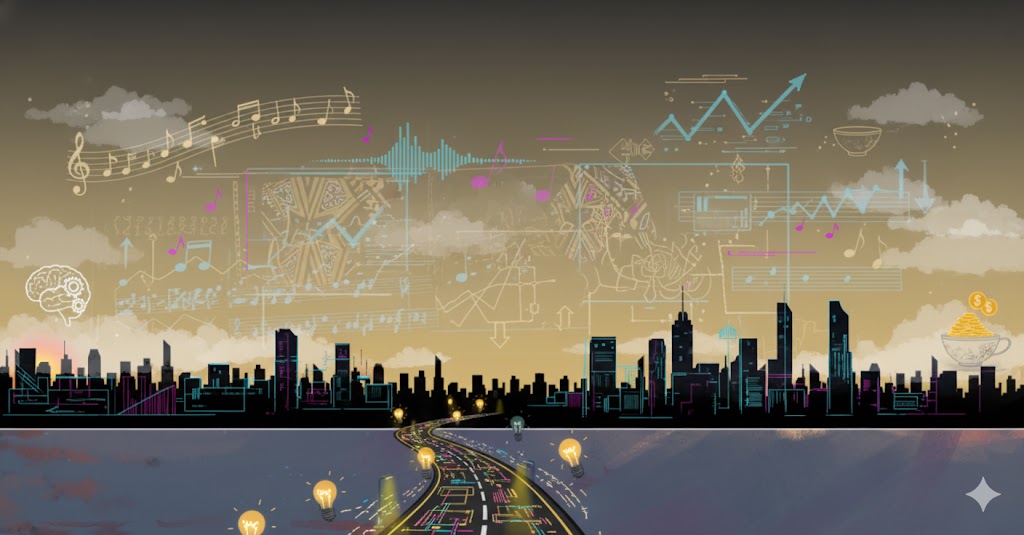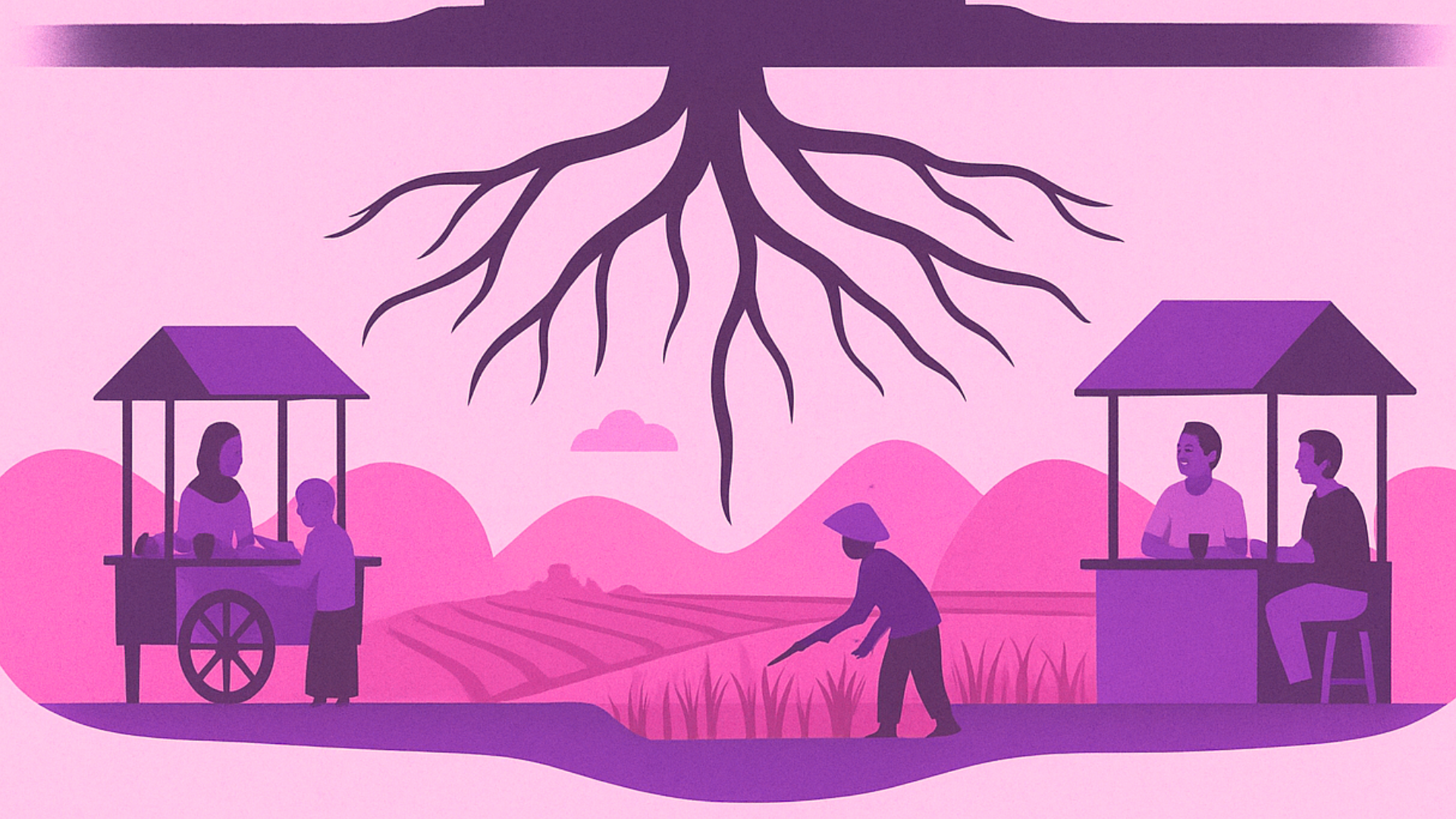KATANYA – Hari Kebudayaan seharusnya menjadi ruang untuk merefleksikan kembali arah dan makna kebudayaan nasional kita. Namun di Lombok, refleksi itu justru memunculkan kembali perdebatan lama: tentang posisi Kecimol (Kesenian Cilokaq Modern Lombok)—satu bentuk kesenian rakyat yang telah lama hidup di tengah masyarakat Sasak.
Sebagai peneliti yang sedang menelusuri dinamika sosial dan kultural Kecimol, saya tidak berkepentingan membela satu pihak. Justru menarik bagi saya untuk melihat perbedaan cara pandang ini sebagai gejala penting—bahwa cara masyarakat memahami “budaya” itu sendiri sedang berubah.
Kalau kita menelusuri jejak Kecimol, mudah terasa bahwa kesenian ini tidak lahir dari ruang seremonial yang megah, melainkan dari kebutuhan yang sangat sederhana: hiburan rakyat. (Dan mungkin di situlah justru letak kekuatannya.)
Di Mapak Belatung, misalnya, seorang pegiat Kecimol yang saya temui—Sahde—menyatakan bahwa “Kecimol muncul karena lebih murah dibanding Gendang Beleq. Cukup tiga juta sudah bisa tampil dengan 20-an pemain, lengkap dengan sound system dan penari.”
Realitas demikian mengandung kenyataan sosial yang tajam: bahwa Kecimol hidup karena terjangkau. Di tengah ekonomi yang pas-pasan, Kecimol menawarkan sesuatu yang dekat, meriah, dan bisa dihadirkan siapa saja tanpa perlu biaya besar. (Ia bukan hanya hiburan, tapi juga jalan ekonomi bagi para pemain, teknisi sound, hingga pedagang kecil di sekitar acara.)
Dalam konteks inilah penting menempatkan Kecimol dalam bingkai ekonomi kreatif lokal. Banyak orang lupa, bahwa sektor seni pertunjukan dan hiburan rakyat adalah bagian nyata dari ekonomi kreatif yang menopang keseharian masyarakat.
Dalam lanskap semacam itu, Kecimol bukan sekadar kesenian jalanan—ia adalah ruang ekonomi rakyat, di mana kreativitas menjadi modal sosial sekaligus sumber penghidupan. Setiap kali satu grup Kecimol tampil, ada perputaran uang: dari jasa pemain, penyewaan alat, penjual makanan, hingga operator sound system. Ekonomi kreatif, dalam pengertian paling konkret, justru hidup di jalanan dan gang-gang kampung semacam ini.
Kecimol, dengan segala dinamikanya, tumbuh di celah antara tradisi dan realitas. Ia tidak hadir untuk menggantikan yang sakral, tapi melengkapi yang sosial; tidak meniru yang lama, melainkan menyesuaikan diri dengan zaman. (Di situlah barangkali letak identitasnya yang paling jujur: bukan “murni tradisi”, tapi tradisi yang terus belajar hidup di dunia yang berubah.)
Dari Cilokaq ke Kecimol: Jejak Evolusi Budaya Populer
Secara historis, Kecimol tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil transformasi panjang dari bentuk-bentuk hiburan rakyat seperti Cilokaq dan Ciledut (Cilokaq Dangdut), hingga berkembang menjadi format Kecimol modern yang kita kenal sekarang.
Instrumennya pun beragam—mulai dari keyboard, gitar, bass elektrik, suling bambu, hingga drum digital dan tamborin. Tak jarang, musik tradisi lokal berdialog dengan lagu dangdut, pop, bahkan remix modern.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa budaya rakyat kini bertransformasi ke ruang digital, membuka akses baru bagi masyarakat untuk mengarsipkan dan menyebarkan praktik budayanya sendiri. Dalam konteks teori budaya, hal ini selaras dengan pandangan Michel de Certeau (1984) bahwa praktik kebudayaan rakyat adalah bentuk “taktik bertahan hidup”—sebuah cara masyarakat menegosiasikan ruangnya dalam arus dominasi modernitas. Maka, keberadaan Kecimol bisa dipahami sebagai resistensi kreatif, bukan penyimpangan dari nilai tradisi.
Kritik yang kerap muncul terhadap Kecimol adalah bahwa ia “terlalu vulgar” dan “tidak mencerminkan nilai-nilai religius masyarakat Sasak.” Kritik semacam ini wajar, terutama jika kita melihat bahwa masyarakat Lombok memiliki akar religiusitas yang kuat. Namun perlu dicatat, budaya tidak pernah berhenti pada satu bentuk final.
Sebagaimana dijelaskan oleh antropolog Clifford Geertz (1973), kebudayaan adalah “jaring makna” yang terus ditenun ulang. Artinya, ekspresi budaya selalu berubah mengikuti konteks sosialnya.
Kecimol adalah wujud dari masyarakat yang sedang bernegosiasi antara tradisi dan modernitas, antara nilai religius dan kebutuhan ekspresi. Ia mungkin bising, penuh improvisasi, bahkan tak jarang menuai kontroversi—tetapi justru di situlah tanda bahwa budaya masih hidup.
Dalam momentum seperti Hari Kebudayaan, pemerintah seharusnya melihat Kecimol bukan sebagai masalah ketertiban, tetapi sebagai aset ekonomi kreatif berbasis komunitas.
Alih-alih menertibkan dengan pendekatan keamanan, pemerintah daerah dapat mengembangkan model pembinaan yang berbasis partisipasi: pelatihan etika pertunjukan, pengaturan ruang dan waktu tampil, serta dukungan terhadap produksi konten digital.
Dengan cara itu, Kecimol tidak hanya bertahan sebagai ekspresi budaya, tetapi juga berkembang sebagai ekosistem ekonomi lokal yang mandiri—selaras dengan semangat pembangunan ekonomi inklusif NTB.
Sebagai pengamat dari luar komunitas Sasak, saya justru melihat Kecimol sebagai jendela untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapi perubahan. Kecimol menunjukkan bahwa budaya lokal tidak menolak modernitas, tetapi berusaha menjinakkannya—memasukkan unsur global dalam bingkai lokal.
Seperti halnya Dangdut Koplo di Jawa Timur atau Jaipongan di Sunda, Kecimol adalah hasil kreatif dari pertemuan antara nilai tradisi, hiburan massa, dan teknologi.
Hari Kebudayaan seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog antara pemerintah, seniman, dan masyarakat. Bukan untuk mencari siapa yang paling “asli”, melainkan bagaimana kebudayaan dapat terus bertumbuh tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.
Kecimol, dengan segala dinamikanya, menunjukkan bahwa kebudayaan rakyat masih hidup dan berdenyut. Ia mungkin berbeda dari bentuk-bentuk tradisi yang lebih tua, tetapi tetap menjadi ekspresi autentik masyarakat Lombok hari ini.
Maka pertanyaannya bukan lagi, “Apakah Kecimol itu budaya Sasak?” melainkan, “Bagaimana kita memperlakukan Kecimol sebagai bagian dari kehidupan budaya kita hari ini?” Karena kebudayaan sejatinya bukan tentang siapa yang paling murni, tetapi siapa yang mampu menjaga agar ia tetap hidup—dan tetap manusiawi.