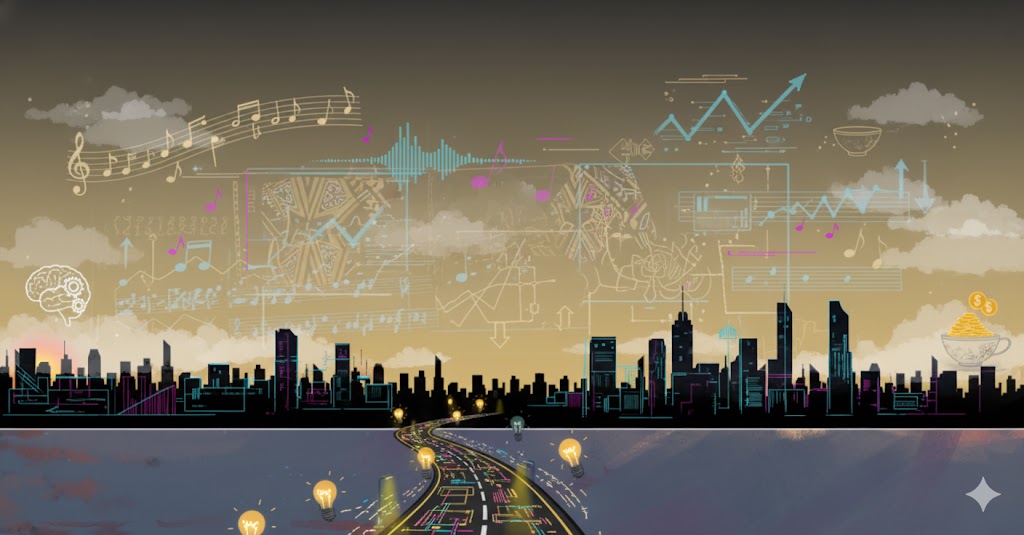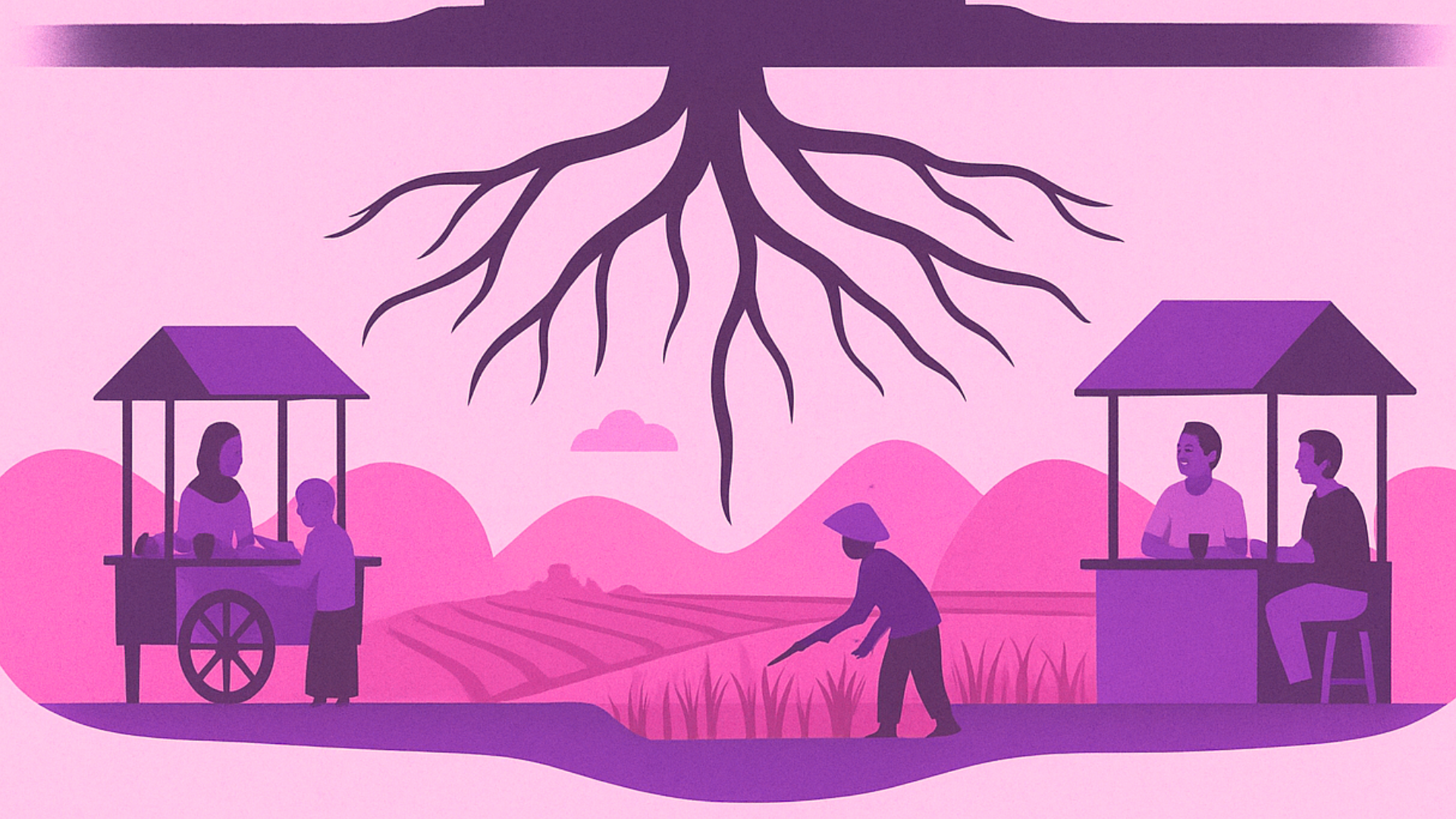Merariq—tradisi penculikan simbolik sebelum perkawinan dalam kehidupan masyarakat Sasak—telah menjadi ruang sakral yang menandai kehormatan, kemandirian pasangan, dan kebijaksanaan adat. Namun dalam dua dekade terakhir, tradisi ini seakan berdiri di persimpangan tajam: antara nilai luhur yang hendak dijaga dan kenyataan baru yang kian tak terelakkan. Merariq tampaknya tak lagi selalu bermakna kematangan moral, tetapi kerap berubah menjadi jalan pintas menuju pernikahan dini—sebuah keputusan yang membawa risiko kesehatan, sosial, dan masa depan perempuan. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut Koentjaraningrat (2009) sebagai “pergeseran makna adat akibat tekanan sosial modern”.
Yang lebih memilukan, persoalan ini tak lagi berhenti pada soal adat atau relasi gender. Ia kini menjelma isu kesehatan publik: angka stunting yang tinggi dan minimnya perlindungan perempuan di tengah perubahan struktur sosial. Merariq—yang dulu menjadi simbol keberanian dan tanggung jawab—kini menghadirkan paradoks yang menuntut kita untuk membaca ulang makna budaya secara lebih jernih.
Modernisasi, media sosial, migrasi, hingga tekanan ekonomi telah menggerus otoritas keluarga dan tokoh adat. Di masa lalu, Merariq dijalankan melalui proses panjang: keluarga saling berunding, tokoh adat memberi nasihat, dan perempuan ditempatkan dalam pusat ritual dengan penuh kehormatan. Kini, proses itu sering hanya menyisakan simbol. Seseorang bisa “lari” hanya dengan kesepakatan impulsif, bahkan dalam hitungan jam, tanpa kesiapan psikologis, finansial, maupun biologis.
Orang tua yang terlalu terkejut atau malu biasanya memilih menerima keadaan. Adat, yang seharusnya melindungi, justru menjadi justifikasi untuk melanggengkan keputusan yang prematur. Ketika seorang perempuan “sudah dibawa”, resepsi adat dan pernikahan formal hampir tak dapat ditolak. Di sinilah “kesakralan” Merariq menjadi pedang bermata dua.
Akibatnya jelas: pernikahan dini meningkat, pun halnya dengan lonjakan kasus stunting. Banyak anak lahir dari pasangan yang belum siap secara ekonomi dan kesehatan, dan perempuan muda menghadapi risiko kehamilan tinggi, anemia, serta lemahnya daya tawar dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan laporan UNICEF (2022) yang menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor paling signifikan yang meningkatkan risiko stunting dan komplikasi kehamilan pada remaja perempuan.
Membaca realitas ini di Lombok Timur memperlihatkan perubahan Merariq yang tengah meniti laku pada proses melemahnya adat. Ia menjadi satu gejala pergeseran struktur sosial-budaya. Modernisasi tidak sepenuhnya menghapus adat; ia justru menciptakan irisan-irisan baru yang membingungkan posisi perempuan. Dalam konteks ini, pandangan Sherry Ortner (1996) mengenai subordinasi perempuan dalam struktur simbolik budaya terasa menemukan relevansinya: perempuan sering dijadikan representasi nilai adat, tetapi tidak selalu diberi posisi menentukan dalam prosesnya.
Dalam diskusi bersama tokoh adat, tokoh agama, perempuan muda, dan pemerintah daerah, muncul satu benang merah yang sangat jelas: perempuan masih belum menjadi subjek penuh dalam pengambilan keputusan adat. Mereka sering dianggap objek—simbol kehormatan, simbol kesucian, simbol rumah tangga—tetapi jarang dilibatkan dalam proses perundingan. Padahal, masa depan merekalah salah satunya yang dipertaruhkan.
Di banyak kasus, perempuan muda mengakui bahwa mereka tidak benar-benar “melarikan diri”, melainkan merasa didorong oleh lingkungan, pasangan, bahkan tekanan digital dari media sosial. Merariq kehilangan unsur kontrol sosial yang dulu menjadi jaring pengaman. Kini, justru ruang itulah yang paling rapuh.
Dari rangkaian temuan tersebut, satu pertanyaan besar menggema: Dapatkah Merariq direvitalisasi tanpa kehilangan esensinya, sekaligus menjawab persoalan stunting dan ketidaksetaraan gender? Jawabannya sangat mungkin.
Revitalisasi bukan berarti memutus tradisi atau menghapus identitas budaya. Ia adalah proses menghidupkan kembali, bukan mengganti. Justru di tanah-tanah adat yang kuat, revitalisasi sering melahirkan inovasi sosial paling besar. Upaya ini akan lebih kuat bila dilakukan melalui pendekatan lintas sektor—menggabungkan adat, kesehatan, gender, dan kebijakan publik dalam satu kerangka utuh. Di banyak daerah, kolaborasi semacam ini terbukti efektif; WHO (2020), misalnya, menegaskan pentingnya integrasi pendekatan budaya dalam strategi kesehatan masyarakat untuk mengatasi stunting dan kesehatan reproduksi.
Dengan membaca ulang nilai dasar Merariq, memperkuat peran perempuan, dan menghadirkan sinergi antara adat dan kebijakan publik, Lombok Timur memiliki peluang besar menjadikan Merariq bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi. Tradisi tidak harus bertentangan dengan kemajuan—kadang justru menjadi pintu masuk yang paling kuat untuk perubahan sosial yang lebih adil, sehat, dan manusiawi.
Merancang Model Revitalisasi
Dalam rancangan awal revitalisasi Merariq yang mulai disusun, muncul tiga gagasan besar yang saling terhubung satu sama lain. Semuanya berangkat dari keinginan sederhana: bagaimana menjaga tradisi tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya.
Gagasan pertama lahir dari kesadaran bahwa pencegahan pernikahan dini adalah jalan paling masuk akal untuk menekan angka stunting. Berbagai riset menunjukkan bahwa kehamilan pada usia terlalu muda meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan gagal tumbuh (UNICEF, 2023). Ketika pasangan menikah pada usia yang cukup, setelah melalui pengecekan kesehatan dan konsultasi pranikah, peluang anak lahir sehat jauh lebih besar. Tradisi tetap berjalan, tetapi dijalankan dalam kerangka kesiapan yang matang—bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Dengan cara itu, adat tetap dihormati, sementara kesehatan publik juga mendapat perlindungan.
Dari sana, mengalir gagasan kedua: perlunya mengembalikan perempuan sebagai subjek penting dalam proses Merariq. Selama ini, terlalu sering perempuan berada pada posisi pasif, seolah-olah mereka hanya bagian dari “alur cerita” yang sudah ditentukan. Padahal merekalah yang hidup dalam konsekuensi tradisi ini. Karena itu, perempuan perlu hadir dalam pembicaraan adat, memiliki ruang untuk menyatakan setuju atau menolak, dan diberi hak penuh untuk memutuskan. Bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai inti dari proses Merariq itu sendiri. Banyak studi antropologi justru menegaskan bahwa perempuan adalah aktor penting yang menentukan legitimasi sebuah praktik adat, termasuk dalam masyarakat Lombok (Bennett, 2005).
Gagasan ketiga kemudian menyatukan semuanya: bagaimana nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam Merariq dapat bersanding harmonis dengan kebijakan perlindungan anak, kesehatan, dan pembangunan sosial. Intinya, Merariq seharusnya menjadi ruang moral yang menjaga kesejahteraan keluarga. Ketika nilai ini dikuatkan, adat justru bisa menjadi sekutu penting bagi program kesehatan masyarakat dan upaya membangun masyarakat yang lebih setara.
Pada titik itu, revitalisasi Merariq bukan hanya tentang memperbaiki cara kita menjalankan tradisi, tetapi juga tentang membayangkan kembali bagaimana adat bisa menjadi kekuatan yang memperkuat masa depan.
Rancangan model ini bukan sekadar konsep akademik; ia lahir dari kegelisahan masyarakat sendiri, dari suara-suara perempuan, dari kecemasan tokoh adat tentang merosotnya wibawa tradisi, dan dari keprihatinan pemerintah yang menghadapi angka stunting tahunan.
Namun revitalisasi bukan tanpa tantangan. Ada resistensi—baik dari mereka yang ingin mempertahankan bentuk Merariq apa adanya, maupun dari kelompok yang ingin menghapus tradisi tersebut sama sekali. Keduanya sering lupa bahwa tradisi selalu bergerak; ia bukan monumen beku.
Dalam sejarah panjang Sasak, Merariq telah mengalami banyak perubahan. Jika dulu ia menjadi mekanisme penyatuan keluarga, dalam konteks kolonial ia berubah menjadi simbol perlawanan. Dalam konteks modern, ia justru menjadi ruang negosiasi identitas baru. Artinya, revitalisasi bukanlah hal yang asing dalam sejarah Merariq—ia bagian dari siklus budaya itu sendiri.
Yang dibutuhkan adalah keberanian dan kemauan kolektif untuk membaca ulang nilai yang paling mendasar dari Merariq: perlindungan perempuan, kehormatan keluarga, dan tanggung jawab sosial. Jika nilai-nilai itu dikembalikan ke posisi utama, stunting bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi peringatan moral bagi komunitas.
Revitalisasi Merariq bukan semata pekerjaan akademis atau proyek pemerintah. Ia adalah upaya menghidupkan kembali tradisi dengan kesadaran baru—tradisi yang mampu merangkul nilai masa kini tanpa kehilangan akar budayanya.
Di tengah gempuran modernisasi, masyarakat Sasak tidak sedang kehilangan identitas. Mereka justru sedang diberi kesempatan untuk memaknai ulang identitas tersebut dengan cara yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih manusiawi.
Jika Merariq kembali menjadi ruang yang melindungi, tidak membahayakan; memberdayakan, bukan membungkam; maka tradisi ini dapat berdiri tegak sebagai warisan budaya yang mampu menjawab tantangan zaman.
Karena pada akhirnya, tradisi yang bertahan bukanlah tradisi yang keras kepala—melainkan tradisi yang mampu bertransformasi tanpa kehilangan jiwanya. Dan Merariq, hari ini, berada tepat di titik krusial itu: sebuah persimpangan antara masa lalu yang hendak kita hormati dan masa depan yang ingin kita ciptakan bersama.