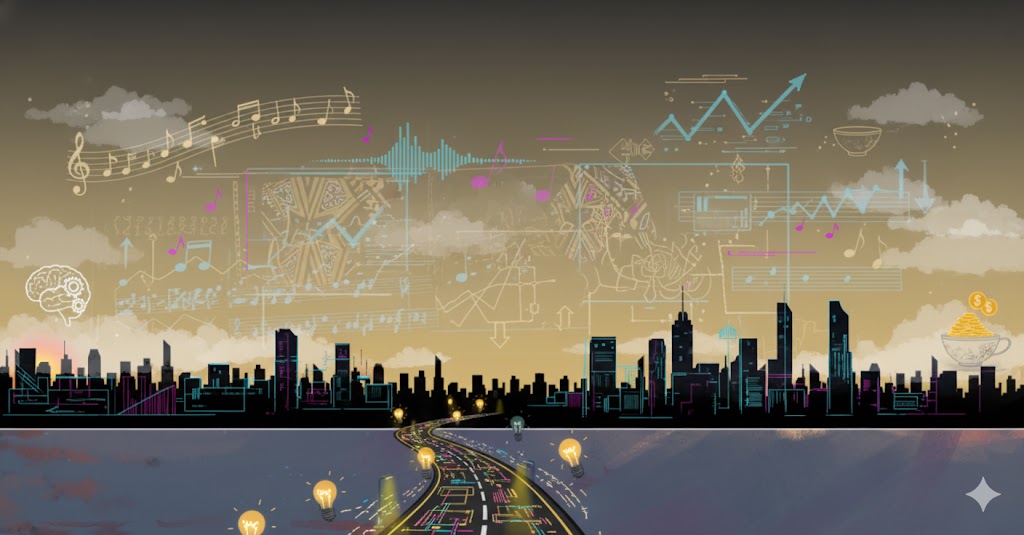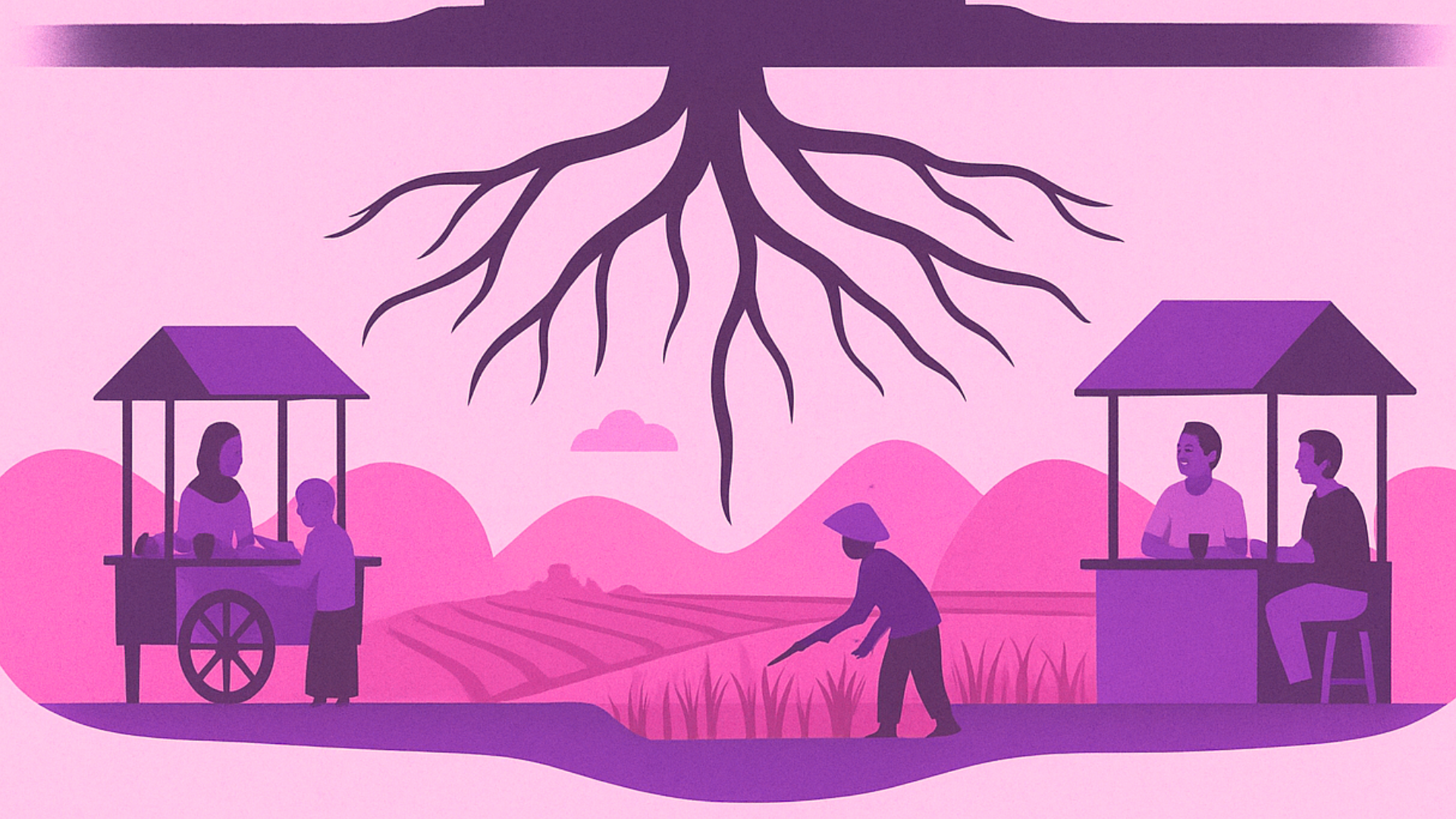Musim Menanam Budi
Matahari di langit Karang Tengah terasa lebih menyengat dari biasanya, namun debu yang beterbangan di tanah gersang itu tak menyurutkan senyum di wajah Mantra. Ia berdiri di atas podium yang dibalut kain hijau zamrud—warna kebanggaan Lembaga Keuangan "Bumi Amanah". Di belakangnya, sebuah baliho raksasa menampilkan wajah Sang Pelindung yang sedang menatap cakrawala dengan gagah, lengkap dengan slogan: Menuju Nusa Paradiso Gemilang.
Mantra merapikan peci hitamnya, lalu berdehem. Suaranya bariton, empuk, dan penuh wibawa—jenis suara yang membuat orang-orang kecil merasa aman.
"Bapak dan Ibu sekalian," suaranya menggema melalui pengeras suara yang sedikit sember. "Kami datang bukan sebagai bankir yang ingin menjerat leher kalian dengan bunga. Kami datang sebagai saudara. Program Kredit Tanpa Bunga ini adalah amanah langsung dari Sang Pelindung. Beliau tidak ingin melihat ada petani yang meminjam ke tengkulak. Gunakan uang ini, kembangkan usaha kalian, dan ingatlah... pemerintah selalu ada di belakang kalian."
Gemuruh tepuk tangan pecah. Seorang nenek renta di barisan depan menyeka air mata, merasa doa-doanya terkabul. Di atas panggung, Mantra menyerahkan sebuah papan sterofom besar berbentuk cek senilai ratusan juta rupiah kepada perwakilan kelompok tani. Kamera wartawan lokal berkilatan, menangkap momen "kebaikan" yang sempurna itu.
Namun, begitu acara seremoni usai dan debu mobil pejabat mulai menjauh dari lokasi, suasana berubah. Mantra masuk ke dalam mobil SUV hitamnya yang dingin oleh AC. Di dalam, sudah menunggu dua orang pria dengan kulit gelap terbakar matahari—para calo lapangan paling berpengaruh di kabupaten itu.
"Bagaimana, Pak Manajer? Respon warga luar biasa," ujar salah seorang pria sambil menyodorkan sebotol air mineral dingin.
Mantra melonggarkan dasinya, sorot matanya yang tadi hangat kini berubah menjadi sedingin es di tangannya. Ia mencondongkan tubuh ke depan.
"Lupakan soal usaha tani mereka," bisik Mantra, suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin mobil. "Aku butuh angka. Target kita ribuan nasabah sebelum akhir tahun. Sang Pelindung butuh 'suara' yang solid di Karang Tengah untuk musim depan. Logistik kampanye tidak bisa menunggu prosedur bank yang bertele-tele."
Pria itu ragu sejenak. "Tapi Pak, banyak dari mereka yang tidak punya lahan, bahkan sebagian hanya pedagang asongan yang KTP-nya kita kumpulkan..."
Mantra tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di atas podium. Ia menepuk bahu pria itu dengan pelan namun menekan.
"Kumpulkan saja KTP-nya. Masukkan ke dalam karung. Jangan terlalu peduli mereka punya sawah atau tidak. Soal verifikasi, itu urusanku di Menara Hijau. Biarkan uang itu mengalir ke bawah sebagai 'sedekah'. Jika nanti mereka tidak bisa bayar, kita sebut saja itu risiko ekonomi rakyat. Kita punya cara untuk 'menghapus dosa' mereka di pembukuan nanti."
Mobil melaju membelah padang gersang Karang Tengah. Di belakang mereka, warga masih menggenggam brosur pinjaman dengan penuh harapan, tanpa menyadari bahwa nama-nama mereka baru saja dimasukkan ke dalam jaring laba-laba raksasa yang sedang ditenun oleh sang manajer.
Di Nusa Paradiso, musim menanam budi telah dimulai. Dan Mantra tahu betul, budi yang ditanam dengan uang negara adalah investasi yang paling sulit ditagih, namun paling mudah dikonversi menjadi kuasa.
Panggung Debu dan Balapan
Tahun 2023 adalah tahun yang bising bagi Provinsi Nusa Paradiso. Deru mesin motor berkapasitas besar menggelegar di sirkuit baru yang dibangun di pesisir pantai. Sang Pelindung berdiri di tribun kehormatan, melambaikan tangan dengan bangga ke arah kamera. Di sekeliling lintasan, umbul-umbul Lembaga Keuangan "Bumi Amanah" berkibar jumawa. Nama bank itu terpampang di mana-mana sebagai sponsor utama, seolah-olah tumpukan uang di brankasnya tak akan pernah habis untuk mendanai mimpi-mimpi besar sang penguasa.
Namun, beberapa ratus kilometer dari kegemerlapan sirkuit, di Menara Hijau yang sunyi, keheningan justru terasa mencekam.
Di lantai lima, di sebuah ruangan sempit yang penuh dengan tumpukan map cokelat, seorang auditor muda bernama Aris sedang mengerutkan kening. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, seirama dengan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Ia baru saja menyandingkan seratus berkas pemohon kredit mikro dari wilayah Karang Tengah.
"Gila..." desis Aris pelan.
Ia menemukan pola yang tidak masuk akal. Ratusan nasabah memiliki jenis tanda tangan yang nyaris identik, seolah-olah satu tangan gaib telah menari di atas ratusan lembar formulir itu. Alamat-alamat mereka pun banyak yang mengarah pada lahan kosong atau gudang pupuk yang sudah lama mati. Angka yang tertera di kolom "Selisih Dana" pada layar monitornya menunjukkan nominal yang membuat kepalanya berdenyut: puluhan miliar rupiah menguap, dan itu baru dari satu klaster kecil.
Sementara itu, di ruang kerjanya yang mewah, Mantra sedang berdiri menatap jendela besar yang menghadap ke arah kota. Ia memutar-mutar gelas berisi teh hangat, namun pikirannya tak sehangat minuman itu. Ia baru saja menerima telepon singkat dari Sang Pelindung yang meminta "tambahan dukungan" untuk acara puncak balapan.
Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Asisten pribadinya masuk dengan wajah pucat.
"Pak, tim audit internal mulai masuk ke berkas Karang Tengah. Mereka menemukan banyak NPL (kredit macet) yang tidak terlaporkan. Kabarnya, mereka akan membawa ini ke rapat direksi besok."
Mantra tidak meledak marah. Ia justru tersenyum tenang, jenis senyum yang biasa ia gunakan untuk menenangkan nasabah yang panik. Namun, tangannya mencengkeram gelas teh itu sedikit lebih kuat.
"Panggil Bapak Penjaga Gerbang," perintah Mantra datar. "Katakan padanya, jika Menara Hijau goyang, kursi-kursi di dewan seleksi juga akan ikut patah. Kita perlu melakukan 'Upacara Penghapusan Dosa' besar-besaran sebelum akhir tahun."
Malam itu, Menara Hijau tidak pernah benar-benar gelap. Di ruangan Mantra, mesin penghancur kertas bekerja lembur. Ribuan dokumen direkonstruksi. Kredit-kredit yang macet dibungkus dengan narasi "Restrukturisasi Akibat Bencana Alam" atau "Dampak Krisis Global". Mantra sedang menjahit jaring-jaring baru, memastikan bahwa selisih puluhan miliar itu terlihat seperti "biaya inklusi keuangan" yang mulia di mata publik.
Di luar, debu sirkuit mulai mengendap, namun di dalam Menara Hijau, badai baru saja dimulai. Mantra tahu, balapan yang sesungguhnya bukanlah di lintasan aspal milik Sang Pelindung, melainkan balapan dengan waktu sebelum auditor-auditor muda itu mencium bau busuk dari karung-karung KTP yang ia sembunyikan di bawah karpet kantornya.
Ambisi Sang Manajer
Awal tahun 2024 menyapa Nusa Paradiso dengan udara yang gerah. Bukan karena matahari, melainkan karena desas-desus yang mulai membakar kedai-kedai kopi dari pinggiran Mantra hingga sudut-sudut gersang Karang Tengah. Sebuah angka fantastis mendadak menjadi bumbu paling pedas dalam setiap obrolan: Satu Triliun.
"Satu triliun itu kalau disusun bisa menutupi aspal sirkuit!" seloroh seorang pengunjung kedai sambil membanting koran lokal ke meja. Di halaman depan, terpampang wajah seorang profesor hukum dengan kacamata tebal, menunjuk ke arah gedung kejaksaan dengan judul bombastis: Laporan Resmi Mengalir, Menara Hijau Diambang Badai.
Di kantornya, Mantra mendengar suara riuh rendah dari televisi yang menyala tanpa suara. Ia mematikan layar dengan remot, lalu bersandar pada kursi kulitnya yang empuk. Keringat dingin sebesar biji jagung sempat muncul di pelipisnya, namun ia segera mengusapnya dengan sapu tangan sutra. Bagi orang biasa, laporan ke jaksa adalah lonceng kematian. Namun bagi Mantra, ini adalah isyarat untuk "melompat lebih tinggi."
"Pak, situasinya makin liar di media sosial," lapor sekretarisnya dengan suara bergetar. "Netizen mulai menghubungkan kredit macet di Karang Tengah dengan nama Bapak."
Mantra justru tertawa kecil. Tawa yang kering dan tajam. "Biarkan saja. Di negeri ini, cara terbaik mematikan isu adalah dengan membuat isu yang lebih besar. Siapkan mobil, kita ke percetakan sekarang."
Beberapa minggu kemudian, publik Nusa Paradiso dikejutkan dengan pemandangan baru. Di persimpangan jalan paling strategis di Kabupaten Karang Tengah, berdiri baliho-baliho raksasa yang menyaingi baliho Sang Pelindung. Di sana, Mantra tampil mengenakan jas rapi dan senyum paling tulus yang bisa ia buat. Slogannya singkat namun menusuk: Penerus Harapan Rakyat, Menanam Budi untuk Masa Depan.
Mantra tidak membela diri di ruang interogasi; ia justru berkampanye di alun-alun.
"Uang yang mereka sebut hilang itu," seru Mantra di depan ribuan warga Karang Tengah dalam sebuah safari politik, "sebenarnya ada di kantong-kantong kalian! Itu adalah modal yang saya perjuangkan agar kalian bisa makan! Sekarang, saat bank ingin menariknya kembali dengan kejam, apakah kalian akan diam? Jika saya jadi pemimpin kalian, saya pastikan tidak ada petani yang dikejar-kejar penagih utang!"
Masyarakat bersorak. Bagi mereka yang memiliki tunggakan kredit "topengan", Mantra adalah mesias yang menjanjikan pemutihan dosa finansial. Di mata rakyat kecil, kredit macet satu triliun itu berubah narasi menjadi "sedekah sang manajer" yang sedang dikriminalisasi oleh lawan politik.
Di balik kemeriahan kampanye itu, Mantra tahu ia sedang berjudi dengan nyawa. Ia menggunakan sisa-sisa wewenangnya di Menara Hijau untuk menginstruksikan para calo lapangan agar memastikan "budi" yang ditanam selama tiga tahun terakhir segera dipanen dalam bentuk loyalitas suara. Ia sadar, jika ia berhasil duduk di kursi kekuasaan, laporan jaksa itu akan berubah menjadi tumpukan kertas tak berarti yang bisa ia kendalikan.
Mantra bukan lagi sekadar manajer bank; ia telah bermetamorfosis menjadi laba-laba yang menggunakan jaring-jaring utang nasabahnya untuk memanjat tangga kekuasaan.
Runtuhnya Tembok Pelindung
Pertengahan tahun 2025 datang seperti musim pancaroba yang membawa badai mendadak. Di Nusa Paradiso, langit yang biasanya biru cerah mendadak terlihat kelabu bagi orang-orang di Menara Hijau. Kabar itu meledak di layar televisi ruang tunggu bank: Bapak Penjaga Gerbang, sang arsitek di balik layar yang menentukan nasib karier ribuan pegawai, digelandang jaksa dengan tangan terborgol.
Ia ditangkap karena skandal pengadaan masker—sebuah kasus yang tak ada hubungannya dengan bank, namun dampaknya meruntuhkan seluruh fondasi yang selama ini menjaga Mantra tetap tegak.
Mantra duduk di meja kerjanya, menatap ponsel yang tak henti-hentinya bergetar. Satu demi satu, nomor-nomor penting yang dulu selalu mengangkat teleponnya dalam satu dering, kini mendadak tidak aktif. Payung raksasa yang selama ini melindunginya dari hujan audit kini robek besar.
Puncaknya adalah malam pemilihan itu. Sang Pelindung, yang selama lima tahun menjadi matahari di Nusa Paradiso, akhirnya kehilangan cahayanya. Hasil penghitungan suara menunjukkan rakyat menginginkan wajah baru. Bagi Mantra, itu bukan sekadar kekalahan politik; itu adalah pengumuman bahwa benteng birokrasi yang melindunginya telah runtuh total.
"Selesai sudah..." gumam Mantra sambil memutar kursi mewahnya, menatap gemerlap lampu kota yang kini terasa asing.
Besok pagi, tim Pansel yang baru akan dibentuk. Direksi baru akan dilantik dengan satu misi tunggal: membersihkan bangkai-bangkai yang membusuk di dalam pembukuan bank. Mantra tahu, auditor OJK sudah mulai mengendus bau anyir dari "KTP dalam karung" di wilayah Karang Tengah. Tanpa perlindungan dari Sang Pelindung dan Penjaga Gerbang, ia hanyalah target empuk di tengah padang terbuka.
Keesokan harinya, Menara Hijau gempar. Ruangan Manajer Kredit Mikro terkunci rapat. Tidak ada dokumen yang tersisa di atas meja. Komputer kantornya bersih, seolah-olah seluruh riwayat digitalnya telah disapu oleh angin malam. Mantra tidak datang untuk mengundurkan diri; ia menghilang begitu saja dalam kesunyian.
Kabar burung segera terbang dengan cepat ke kedai-kedai kopi. Ada yang bilang ia melarikan diri ke luar negeri, ada yang bilang ia bersembunyi di balik jubah pengajian di pinggiran kota, dan ada pula yang menyebut ia telah berpindah baju menjadi seorang akademisi yang tenang, mencoba mencuci namanya di ruang-ruang kuliah.
Kursi Mantra di Menara Hijau kini kosong melompong, hanya menyisakan laci yang terkunci dan aroma parfum mahal yang perlahan memudar. Namun di Karang Tengah, ribuan "KTP dalam karung" yang pernah ia kumpulkan mulai menjadi api dalam sekam yang siap membakar siapa pun yang masih tertinggal di dalam gedung itu. Mantra telah melakukan Ganti Baju di Balik Panggung, meninggalkan panggung yang terbakar menuju sebuah jalan sunyi yang ia rancang sendiri.
Menghapus Jejak, Mengubah Wujud
Di ujung tahun 2025, Karang Tengah tetaplah wilayah yang berdebu, namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Di atas lahan-lahan luas yang dulunya gersang dan terbengkalai, kini berdiri pagar-pagar beton baru. Truk-truk besar bermuatan pupuk dan alat pertanian hilir mudik memasuki gudang-gudang raksasa yang papan namanya masih mengkilap.
Anehnya, tak ada nama Mantra di sana. Di akta notaris perusahaan-perusahaan suplier pupuk itu, tertera nama-nama pemuda desa yang dulu hanyalah calo lapangan, atau kerabat jauh yang bahkan tak paham cara membaca laporan laba-rugi. Mereka adalah nominee—nama-nama pinjaman yang dipasang untuk menutupi wajah asli sang pemilik modal.
Mantra telah berhasil melakukan sulap terbesar dalam hidupnya: mengubah tumpukan "KTP dalam Karung" yang macet di bank menjadi hamparan tanah produktif dan rantai bisnis saprodi yang nyata.
Sementara itu, di sebuah ruko mewah di pusat kota Mantra, sebuah minimarket modern baru saja dibuka. Di lantai dua ruko itu, terdapat kantor kecil bertuliskan "Yayasan Paradiso Madani". Di sanalah sang istri, seorang akademisi yang tampak bersahaja, mengelola sebuah lembaga kajian ekonomi syariah. Yayasan itu terlihat sangat sibuk, menerima hibah-hibah dalam jumlah besar dengan alasan "dana riset" atau "biaya jasa profesional". Tak ada yang curiga bahwa yayasan itu adalah mesin pencuci yang sempurna, tempat di mana uang negara yang telah "dimacetkan" mengalir kembali menjadi pendapatan yang sah dan terlihat suci.
Suatu sore, Mantra duduk di sudut minimarket tersebut. Ia tak lagi mengenakan setelan jas manajer bank yang kaku atau baju safari politik yang penuh debu. Ia mengenakan kemeja linen putih, santai, dan sebuah kacamata hitam yang menutupi tatapan matanya yang tajam. Di tangannya, ia memegang laporan keuangan minimarket dan yayasannya. Semuanya terlihat putih bersih, tak ada noda kredit macet, tak ada selisih satu triliun. Semuanya seolah-olah dibangun dari keringat dan doa.
Ia menyesap kopi mahalnya dengan tenang, memperhatikan orang-orang yang mengantre di kasir. Ia merasa aman. Di matanya, "Menara Hijau" kini hanyalah sebuah kenangan buruk yang telah ia tinggalkan di belakang. Semua jejak digital dan kertas di kantor lamanya mungkin sedang diperiksa habis-habisan oleh tim sapu bersih, namun Mantra yakin jaring-jaringnya sudah tertanam terlalu dalam di tanah Karang Tengah.
Ia telah berhasil menghapus jejak dan mengubah wujud. Dari seorang manajer yang dicurigai sebagai pencuri, menjadi seorang pengusaha dan dermawan yang terhormat. Namun, di balik ketenangannya, Mantra tahu bahwa di luar sana, angin sedang berbalik arah. Di gedung Kejaksaan, seseorang sedang menyusun kepingan teka-teki yang ia tinggalkan, mencari satu saja benang merah yang luput ia putus.
Mantra tersenyum tipis. Baginya, kejahatan yang paling sempurna bukanlah yang tidak meninggalkan jejak, melainkan yang jejaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terlihat sangat mulia.
Sapu Baru dan Ruang Interogasi
Januari 2026 dimulai dengan udara yang sangat dingin di Menara Hijau. Nazar, direktur baru yang dikenal memiliki tatapan sedingin baja, melangkah menyusuri lorong lantai lima. Di tangannya, ia memegang sebuah kunci master. Langkah sepatunya yang tegas bergema, seolah sedang menghitung mundur waktu bagi siapa pun yang pernah bersembunyi di balik dinding ini.
Ia berhenti di depan pintu ruangan yang dulu dihuni oleh Mantra. Dengan satu putaran kunci, pintu terbuka. Nazar disambut oleh ruangan yang tampak sempurna, terlalu sempurna. Meja jati itu mengkilap tanpa sebutir debu pun. Namun, saat Nazar menarik laci meja satu per satu, ia hanya menemukan kekosongan. Laci-laci itu melompong, seolah seluruh sejarah perbankan di ruangan itu telah diuapkan oleh sihir.
"Dia tidak hanya pergi," gumam Nazar sambil meraba permukaan laci yang dingin. "Dia menghapus jejak kakinya sendiri."
Namun, Nazar bukan orang baru dalam urusan "cuci gudang". Di belakangnya, tim audit forensik mulai membongkar server digital. Mereka tidak mencari kertas; mereka mencari jejak digital yang tertinggal dalam cache dan log transaksi yang gagal dihapus. Sementara itu, di Karang Tengah, tim lapangan mulai mendatangi rumah-rumah nasabah. Mereka menemukan fakta pahit: ribuan warga yang tercatat memiliki utang puluhan juta ternyata hanya pernah menerima amplop berisi dua ratus ribu rupiah. "KTP dalam Karung" itu mulai bicara.
Beberapa kilometer dari sana, di sebuah gedung beton dengan gerbang tinggi yang dijaga ketat, seorang jaksa senior sedang menyesap kopi pahitnya. Di atas mejanya, sebuah daftar nama baru saja dicetak. Ia mengambil sebuah pulpen tinta hitam, lalu melingkari sebuah inisial dengan garis yang tebal: M.
"Panggil dia minggu depan," perintah sang jaksa kepada asistennya. "Kita lihat apakah kemampuannya berargumen di atas podium politik sehebat penjelasannya di bawah lampu interogasi."
Mantra berdiri di balkon rumah barunya di perbukitan yang menghadap ke laut lepas. Angin laut memainkan ujung kemeja linennya. Di bawah sana, lahan pertanian yang sangat luas membentang hijau—semuanya miliknya, meski tak ada satu pun yang tertulis atas namanya.
Ia tahu, di Menara Hijau, Nazar sedang membongkar laci-lacinya. Ia juga tahu, surat panggilan dengan logo timbangan itu mungkin sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Namun, Mantra hanya tersenyum tipis. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Jaring laba-laba yang ia tenun selama bertahun-tahun telah berubah menjadi benteng beton, bisnis ritel yang ramai, dan dukungan massa yang masih memujanya sebagai pahlawan.
"Benih itu sudah tumbuh," bisiknya pada angin.
Ia menyadari bahwa meski ia mungkin akan duduk di kursi kayu ruang interogasi, uang satu triliun yang "hilang" itu tidak benar-benar lenyap. Uang itu telah bermetamorfosis menjadi kehidupan baru yang akan menjamin tujuh turunannya. Baginya, hukum hanyalah sebuah prosedur administratif, sementara kekayaan yang telah dipindahkan adalah kebenaran yang abadi.
Mantra tetap tenang. Di Nusa Paradiso, ia telah membuktikan satu hal: bahwa di tangan seorang laba-laba yang cerdik, kredit macet bukan hanya soal angka yang merah di laporan keuangan, melainkan tiket untuk membeli kebebasan dan masa depan yang tak tersentuh—selama tak ada satu pun jaring yang terputus.