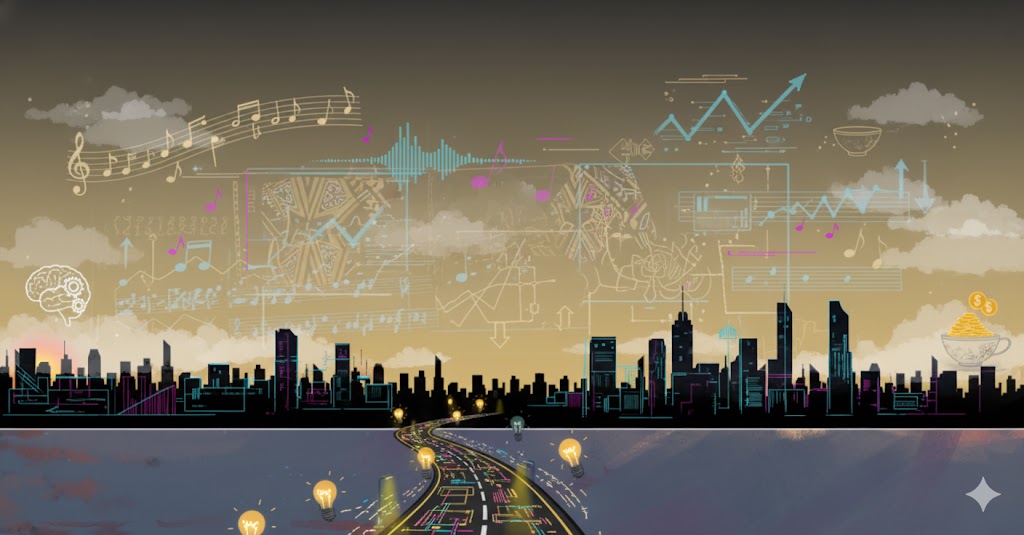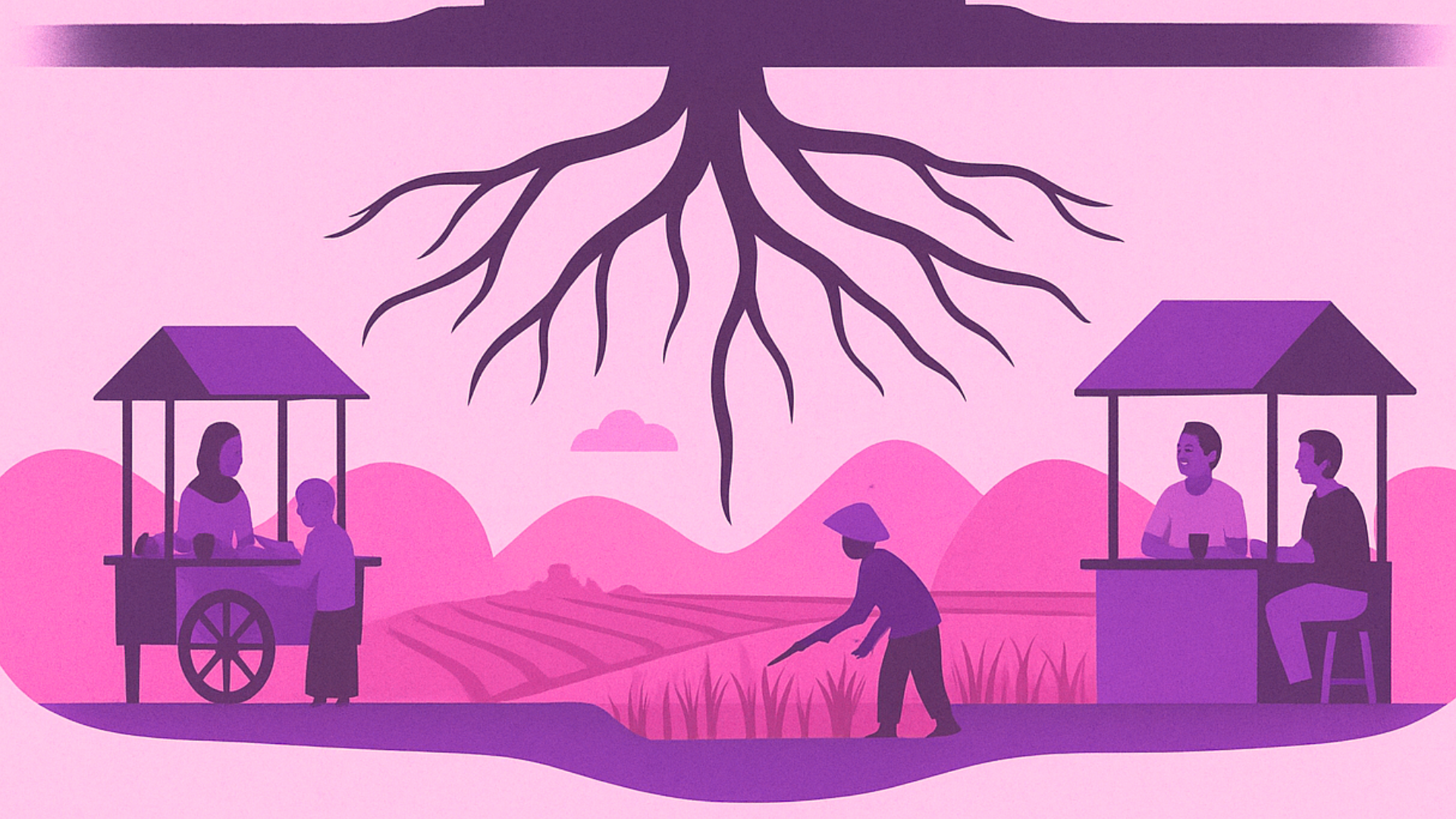KATA-NYA - Taman budaya didirikan dengan cita-cita luhur, untuk menjadi rumah bersama bagi seni dan kebudayaan. Sebuah rumah besar dengan pintu yang terbuka, di mana semua seniman bisa menemukan ruang untuk mengekspresikan diri. Di sana seharusnya tidak ada sekat darah atau garis kedekatan, melainkan semangat kolektif untuk merawat keberagaman. Namun realitas yang hadir tidak selalu seindah utopia. Rumah besar itu kini seperti dikunci, kursi hanya disediakan untuk tamu-tamu tertentu, dan panggung lebih sering menyambut wajah yang sama dari lingkaran yang sempit. Pada titik inilah seni mulai tersisih dari rumahnya sendiri.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari relasi antara seni dan kekuasaan. Mari kita lihat dengan kacamata Sosiologi Seni. Dalam kerangka sosiologi seni, seni tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam pusaran sosial, politik, dan ekonomi. Antonio Gramsci mengingatkan bahwa seni kerap dijadikan instrumen hegemoni. Artinya ia sebagai alat bagi kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan melalui legitimasi kultural. Apa yang kita saksikan di sebagian besar taman budaya di Indonesia hari ini tak lain adalah bentuk kecil dari hegemoni itu: program seni yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat luas malah menyempit menjadi kepentingan segelintir orang, seakan panggung hanyalah perpanjangan dari meja kekuasaan.
Pierre Bourdieu pun menyebut seni sebagai “arena pertarungan simbolik”, tempat berbagai aktor berebut modal budaya. Ketika akses ke panggung dibatasi, ketika kurasi program tidak transparan, maka modal budaya hanya beredar di lingkaran yang sama. Seniman dan komunitas yang berada di luar lingkaran kekuasaan kehilangan kesempatan untuk tampil, kehilangan legitimasi, bahkan kehilangan identitas sebagai bagian dari ekosistem budaya. Padahal, sebagaimana kita pahami, seni bukan sekadar ekspresi estetis, tetapi juga sarana untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah struktur sosial.
Dampak dari praktik seperti ini jelas. Seniman kecil, komunitas lokal, atau kelompok muda yang berusaha mencari ruang justru tersisih. Mereka akhirnya harus menggelar pertunjukan di kafe kecil, di ruang alternatif, bahkan di jalanan. Ironinya, gedung megah taman budaya dengan lampu terang sering kosong dari keberagaman, sementara ruang-ruang alternatif justru bergemuruh dengan energi kreatif. Publik pun kehilangan kesempatan untuk menikmati kekayaan seni yang seharusnya hadir di rumah besar tadi.
Di sinilah luka itu terasa. Seni, yang seharusnya menjadi milik bersama, terpinggirkan oleh politik distribusi panggung. Masyarakat hanya disuguhi menu yang sama, seolah-olah seni hanya milik mereka yang dekat dengan kekuasaan. Dalam bahasa sosiologi seni, situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan budaya bisa berubah menjadi mekanisme eksklusi, bukan inklusi. Padahal, seni dalam sejarahnya justru sering menjadi suara bagi yang tersisih (dari mural protes di Meksiko hingga seni kontemporer yang menantang dominasi pasar global).
Namun seni juga memiliki daya resistensi. Seperti yang diulas dalam teori kritis Adorno, seni seharusnya mampu mengguncang struktur sosial, bukan sekadar mengikutinya. Ketika taman budaya gagal membuka diri, seniman akan mencari cara lain untuk bersuara. Mereka akan membentuk komunitas, menciptakan ruang alternatif, atau menggunakan media digital untuk menjangkau publik. Itulah bukti bahwa seni, meski dikebiri, selalu menemukan jalan untuk hidup.
Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut. Harus ada jalan tengah agar taman budaya kembali menjadi rumah bersama. Pertama, transparansi program mutlak diperlukan: agenda, proses kurasi, hingga alokasi anggaran harus diumumkan secara terbuka. Kedua, sistem kurasi harus melibatkan dewan independen yang menilai karya berdasarkan kualitas, bukan kedekatan. Ketiga, kolaborasi lintas kelompok perlu digalakkan, Antara tradisi dan modern, antara kota dan desa, antara generasi tua dan muda. Dengan begitu taman budaya tidak lagi menjadi ruang eksklusif, tetapi titik pertemuan.
Yang lebih penting, taman budaya harus menegaskan dirinya bukan sebagai “pemilik panggung”, melainkan fasilitator. Ia harus menjadi tuan rumah yang ramah, memberi ruang untuk siapa pun yang ingin berkarya, bukan hanya mereka yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan. Dengan cara itu, seni kembali pada fungsinya: menjadi medium untuk mempertemukan, memperkuat identitas, sekaligus mengkritik struktur sosial yang timpang.
Seni tidak boleh menjadi tamu asing di rumahnya sendiri. Taman budaya, yang dibangun dari jerih payah publik, adalah milik bersama. Ketika ia berubah menjadi halaman pribadi, yang hilang bukan hanya kesempatan seniman, tetapi juga hak masyarakat untuk merayakan keberagaman budaya. Mari kita refleksikan kembali, taman budaya hanya akan hidup jika setiap seniman merasa punya kursi di meja yang sama dan jika seni diakui sebagai agen perubahan sosial.
Seni hanya akan tumbuh subur jika ia diterima sebagai milik bersama dan dirayakan bersama-sama.