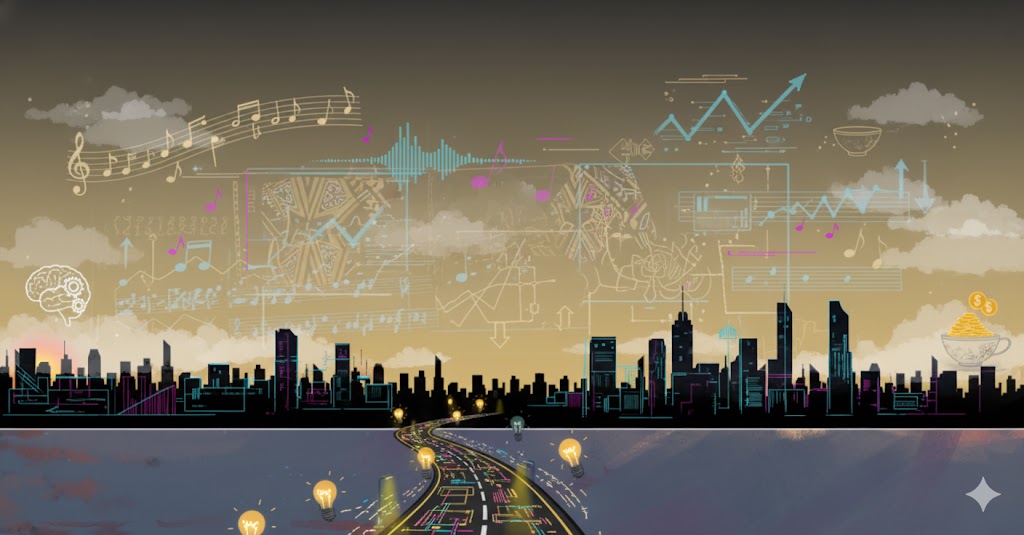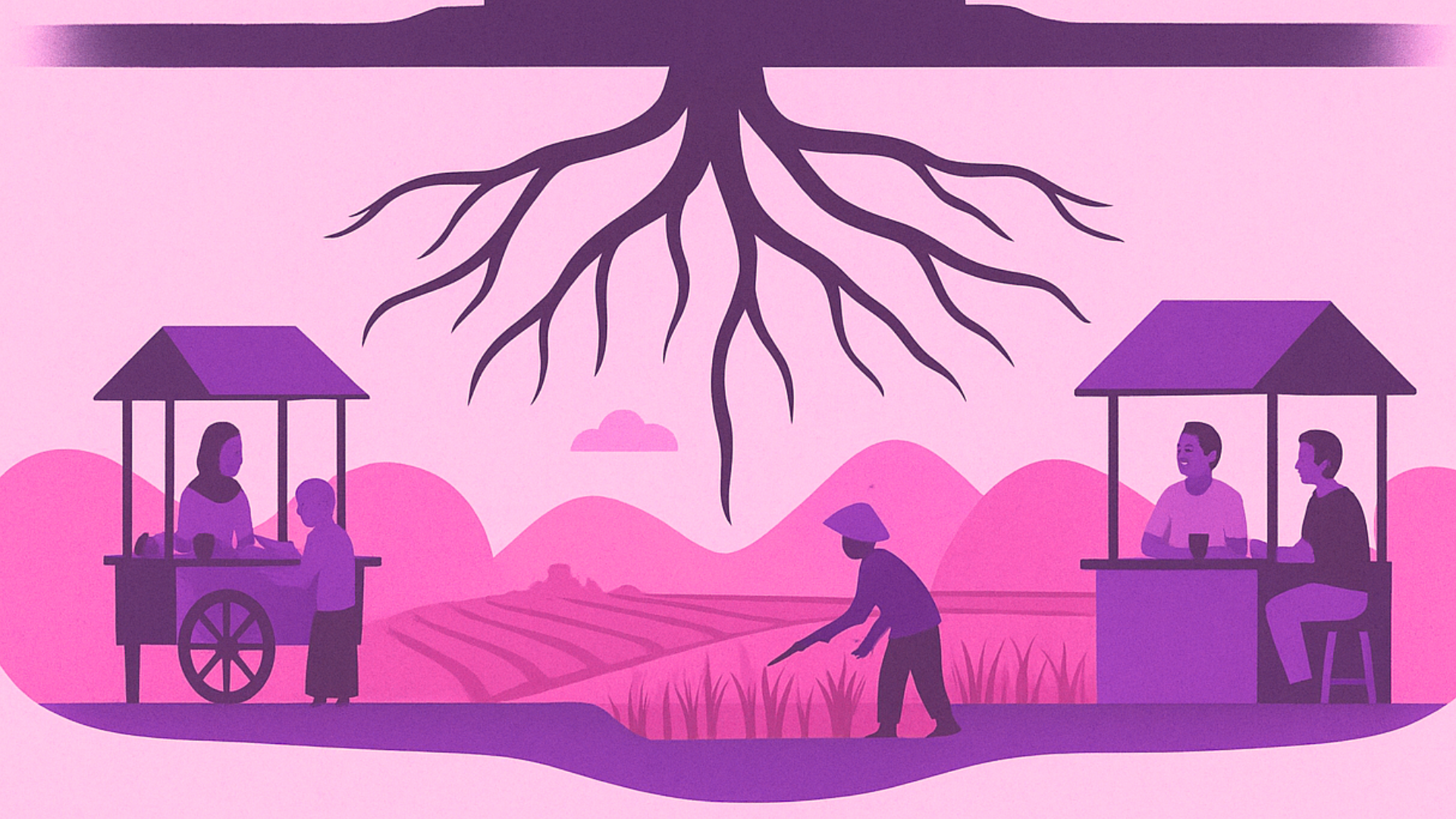KATANYA-Bayangkan Anda sedang bersantai di kafe favorit, menyeruput kopi susu kekinian, ditemani alunan suara... kicau burung. Bukan karena kafe itu pindah ke tengah hutan tropis atau sedang kolaborasi dengan komunitas pengamat burung, tapi karena pemiliknya panik—dan memutuskan bahwa suara burung lebih aman daripada putar musik. Aneh? Justru lumrah, di era di mana para pelaku usaha berebut “jalan ninja” untuk menghindari aturan royalti musik yang makin membingungkan.
Dari Jakarta hingga Denpasar, banyak kafe kini tampil dengan suasana baru: tanpa musik. Playlist Spotify yang dulu setia menemani obrolan malam kini digantikan gemericik air sungai, desir angin, atau denting lonceng angin bambu. Beberapa bahkan nekad memutar lagu-lagu asing dengan asumsi bahwa Ed Sheeran tak mungkin sempat menagih royalti ke warung kopi di Karawang.
Tapi tunggu dulu—Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hadir membawa pencerahan sekaligus kejutan: bahkan suara kicau burung pun kena royalti, asalkan direkam secara profesional dan diputar untuk kepentingan komersial. Ya, burung juga bisa jadi subjek hukum. Selamat datang di republik di mana seekor burung bisa lebih dulu mengklaim hak cipta dibanding sebagian seniman indie.
Kabar baiknya? Burung tidak bisa menuntut langsung ke pengadilan. Kabar buruknya? Produser rekamannya bisa. Dan itulah titik awal masuk ke labirin hak cipta yang tak hanya membingungkan, tapi juga bikin pelaku usaha mendadak jadi ahli hukum—spesialis kursi, lisensi, dan suara daun jatuh.
Kekacauan ini mencapai klimaksnya ketika sebuah nama besar di dunia kuliner—Mie Gacoan Bali—tersandung kasus royalti. Direktur gerainya, I Gusti Ayu Sasih Ira, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali karena dianggap lalai membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di restorannya sejak 2022. LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) menyebut angka kerugian yang muncul tak main-main: miliaran rupiah.
Bagi para musisi, ini seperti menemukan oasis di tengah padang gurun: akhirnya ada tindakan nyata untuk menegakkan hak mereka. Tapi bagi pelaku usaha, terutama di sektor kuliner, kasus ini seperti disambar petir di siang bolong—cepat, menyakitkan, dan membingungkan.
Apalagi jika melihat tarif royalti yang diberlakukan: Rp60.000 per kursi per tahun. Sekilas terdengar kecil, tapi bagi kafe mungil dengan 10 kursi, totalnya bisa menyamai harga satu mesin espresso bekas—alat vital yang justru mendatangkan penghasilan. Di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi, beban tambahan ini terasa seperti memaksa pelaku usaha memilih antara putar musik atau tetap bertahan hidup. Ironisnya, keputusan seperti itu bukan soal estetika ruang, tapi soal bertahan dalam sistem yang belum semua orang pahami.
Respons pelaku usaha atas kasus Mie Gacoan menyebar cepat, dan reaksinya beragam—mulai dari konyol, kaku, hingga menyerah total. Beberapa kafe memilih solusi paling aman: sunyi. Musik dimatikan sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah Q Food & Music di Jakarta, yang semula dikenal sebagai tempat makan sekaligus tempat menikmati musik, kini nyaris tanpa suara selain sendok dan garpu beradu. Suasananya berubah drastis—lebih menyerupai ruang baca daripada tempat nongkrong.
Yang lain mencoba menghindar dengan memutar lagu-lagu asing, berasumsi bahwa musik dari luar negeri tak masuk hitungan. Mereka mungkin berharap musisi global seperti Ed Sheeran atau Taylor Swift tak akan mempermasalahkan lagu mereka diputar di sudut-sudut kafe Indonesia. Tapi LMKN dengan cepat membantah ilusi ini: Indonesia sudah menjadi bagian dari konvensi internasional seperti WIPO, sehingga kewajiban royalti berlaku pula untuk karya musisi mancanegara.
Ada juga yang mengambil jalur “netral” dengan memutar rekaman suara alam: hujan, angin, atau kicau burung—berharap itu bisa jadi celah aman. Namun, LMKN kembali menegaskan bahwa rekaman suara alam, jika digunakan secara komersial dan berasal dari produksi profesional, tetap memiliki perlindungan hak cipta. Situasi ini membuat pelaku usaha kebingungan: memutar musik salah, tak memutar pun kehilangan suasana. Akhirnya, banyak yang memilih diam. Kafe jadi sunyi. Musik mati gaya.
Tiba-tiba, cahaya kecil muncul dari tribun sepak bola. Klub Persebaya Surabaya menyatakan anthem mereka, Song For Pride, bebas diputar oleh kafe dan warung kopi tanpa bayar royalti. Publik bersorak. Tapi di balik euforia itu muncul pertanyaan menohok: jika Persebaya bisa, kenapa yang lain tidak? Mengapa sistem royalti nasional begitu kaku hingga pelaku usaha lebih memilih keheningan daripada lagu karya anak bangsa?
Masalahnya Bukan Musik, Tapi Mesin Aturannya
Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan semangat undang-undang. UU Hak Cipta dan PP Royalti memang lahir untuk membela musisi, pencipta lagu, dan produser. Pada 2023, LMKN bahkan berhasil mengumpulkan Rp55,2 miliar royalti, dengan target Rp120 miliar tahun berikutnya. 79% dari angka itu diklaim disalurkan ke pemilik hak. Tapi tunggu dulu—berapa banyak pelaku usaha kecil yang paham cara menghitung royalti berdasarkan jumlah kursi? Apakah mereka tahu ke mana uang itu mengalir?
Transparansi adalah lubang menganga. Bukan hanya pelaku usaha, para musisi pun banyak yang mengaku bingung: lagu mereka sering diputar, tapi uang yang masuk malah seperti recehan parkir.
Lebih parah lagi, aturan ini seperti muncul dari balik kabut. Pelaku usaha, terutama skala kecil, menganggap musik cuma pemanis suasana—bukan urusan hukum. Tiba-tiba, datang petugas meminta bayaran berdasarkan jumlah kursi. “Tapi bang, dua kursi saya patah!” barangkali jadi keluhan yang makin sering terdengar. Namun hukum tak mengenal empati. Putar musik, bayar royalti. Titik.
Kebingungan ini perlahan berubah jadi ketakutan. Media sosial sudah ramai dengan gerakan tak resmi: "anti-royalti". Banyak pelaku usaha merasa lebih aman memutar lagu asing atau bahkan tidak memutar musik sama sekali. Ironisnya, aturan yang dibuat untuk memajukan musik Indonesia justru bikin lagu-lagu lokal ditinggalkan. Jika ini dibiarkan, musisi seperti Hindia atau Pamungkas mungkin akan kehilangan salah satu panggung paling organik mereka: kafe dan warkop.
Dan kalau Anda kira kekacauan ini cuma antara pelaku usaha dan LMK/LMKN, salah besar. Di balik panggung, para musisi juga ribut sendiri. Dari Fanny Soegi yang berseteru dengan tim produksi Asmalibrasi, Agnez Mo yang dituntut oleh Ari Bias, hingga Ahmad Dhani yang melarang Once menyanyikan lagu Dewa—semua menunjukkan bahwa di ranah hak cipta, harmoni belum tentu datang dari musisi itu sendiri. Kalau yang besar saja bingung, bagaimana nasib para musisi indie yang royalti streaming-nya tak cukup untuk beli mie instan?
Jadi, bagaimana kita keluar dari kekacauan ini? Pertama, transparansi harus jadi prinsip utama. LMKN perlu membuka data aliran royalti secara publik. Kedua, edukasi yang kreatif. Daripada seminar sepi peserta, kenapa tidak kampanye TikTok dengan musisi lokal yang menjelaskan pentingnya royalti—tanpa membuat pelaku usaha merasa ditagih utang?
Ketiga, skema fleksibel untuk UMKM. Daripada hitungan per kursi yang bikin pening, kenapa tidak bikin paket langganan bulanan royalti, seperti langganan Wi-Fi? Terakhir, digitalisasi. Cukup dengan satu platform, pemilik usaha bisa cek, bayar, dan lapor royalti tanpa harus dikejar-kejar petugas seperti penagih hutang.
Langkah Persebaya bisa jadi inspirasi. Musisi atau label bisa membuat lagu-lagu “gratis royalti” untuk kafe komunitas, sebagai bentuk promosi sekaligus dukungan budaya. Atau, bagaimana jika LMKN bekerja sama dengan platform streaming untuk menciptakan playlist “royalty-ready”—playlist legal yang sudah termasuk biaya lisensi dalam paket berlangganan?
Karena pada akhirnya, musik adalah denyut nadi ruang publik. Kafe bukan cuma tempat minum kopi, tapi juga ruang di mana lagu-lagu hidup dan berputar. Kalau kafe hanya menawarkan suara kicau burung atau—lebih buruk lagi—keheningan, maka yang rugi bukan hanya musisi, tapi kita semua.